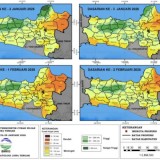TIMES PADANG, PADANG – Pada awal abad ke-20, pembangunan kota memiliki mantra yang nyaris tak terbantahkan: terang dan terhubung. Listrik, telegraf, lalu telepon dipandang sebagai penanda mutlak modernitas. Kota yang baik adalah kota yang menyala dan saling terhubung. Demi mewujudkan cita-cita itu, kabel-kabel dibentangkan dengan penuh optimisme dari satu tiang ke tiang lain, melintas di atas jalan, menyilang gang, dan merangkul sudut-sudut kota.
Solusi ini dianggap paling masuk akal pada masanya murah, cepat, dan efisien. Namun, seiring waktu, pilihan pragmatis itu meninggalkan warisan yang kini kita saksikan setiap hari: langit kota yang kusut oleh anyaman kabel, menyerupai akar liar yang menggantung di udara.
Apa yang dahulu dipuja sebagai simbol kemajuan, kini justru berubah menjadi problem estetika sekaligus teknis. Setiap kemunculan teknologi baru televisi kabel, internet broadband, hingga fiber optik nyaris selalu diikuti dengan satu kebiasaan lama: menambah kabel baru tanpa membereskan yang lama. Tiang-tiang makin sesak, kabel saling tindih tanpa tata kelola yang jelas, sementara kabel usang dibiarkan menggantung seperti artefak yang terlupakan.
Dalam kondisi tertentu, hutan kabel ini bukan hanya merusak pandangan, tetapi juga menghadirkan risiko nyata: putus saat badai, menjadi sarang satwa urban, hingga memicu korsleting dan kebakaran di kawasan padat penduduk. Di hadapan kota yang ingin tampil modern dan layak huni, pemandangan ini menjadi semacam pengakuan diam-diam atas kegagalan pengelolaan ruang publik.
Kesadaran untuk “menjinakkan langit” sebenarnya bukan barang baru dalam sejarah kota-kota dunia. Sejumlah kota besar telah lama menyadari bahwa membiarkan infrastruktur utilitas menggantung di udara adalah solusi sementara yang mahal di masa depan.
Paris dan London, misalnya, mulai memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah seiring geliat Revolusi Industri. Di Paris, penataan ulang kota oleh Baron Haussmann pada abad ke-19 tidak hanya melahirkan boulevard yang megah, tetapi juga sistem terowongan bawah tanah yang rapi, menjaga agar langit kota tetap bersih dan bangunan bersejarah dapat dinikmati tanpa gangguan visual.
Tokyo mengikuti jejak serupa dengan caranya sendiri. Momentum Olimpiade 1964 dimanfaatkan sebagai pemicu modernisasi kota secara besar-besaran, termasuk penataan infrastruktur utilitas. Sementara itu, Singapura menjadi contoh paling konsisten di kawasan Asia. Sejak dekade 1990-an, negara kota ini menerapkan kebijakan tegas: kawasan baru wajib menggunakan kabel bawah tanah. Tidak ada kompromi.
Hasilnya terasa nyata langit kota yang lapang, tertib, dan selaras dengan citra “Kota Taman” yang selama ini dibangun. Namun, pengalaman global juga menunjukkan bahwa perjuangan melawan kabel udara tidak selalu berjalan mulus.
Di kota-kota dengan urbanisasi yang melesat cepat seperti Mumbai atau Manila, hutan kabel justru semakin rapat, mencerminkan pertarungan antara kebutuhan akses murah dan impian tata kota yang tertib.
Indonesia berada di persimpangan yang serupa. Hutan kabel telah menjadi bagian dari identitas visual banyak kota besar. Upaya pembenahan memang ada, tetapi sering kali berjalan sporadis dan terjebak pada simbolisme. Jakarta bisa menunjuk kawasan Sudirman–Thamrin sebagai etalase keberhasilan, namun di luar koridor itu, kabel-kabel masih bergelantungan tanpa ampun.
Persoalan biaya kerap dijadikan alasan utama. Pemindahan kabel ke bawah tanah memang jauh lebih mahal dibandingkan pemasangan kabel udara, bahkan bisa berkali-kali lipat. Di titik ini, perdebatan tentang siapa yang harus menanggung biaya pemerintah, BUMN, atau operator swasta sering berakhir tanpa keputusan tegas.
Masalah lain yang tak kalah pelik adalah kondisi bawah tanah kota-kota kita yang sudah penuh dengan infrastruktur lama, banyak di antaranya tidak terdokumentasi dengan baik. Pipa air, saluran drainase, dan utilitas lain berseliweran seperti benang kusut di bawah permukaan.
Ditambah lagi, mentalitas “tambah saja dulu” masih mendominasi, karena dianggap paling cepat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, mempertahankan pola tambal sulam hanya akan memperpanjang daftar masalah yang diwariskan ke generasi berikutnya.
Indonesia membutuhkan keberanian untuk keluar dari lingkaran pragmatisme jangka pendek. Payung hukum yang kuat dan mengikat lintas sektor menjadi prasyarat mutlak agar penataan kabel tidak sekadar menjadi proyek kosmetik.
Kawasan-kawasan baru harus diposisikan sebagai standar baru, bukan pengecualian. Di saat yang sama, skema pembiayaan kreatif perlu dikembangkan agar beban tidak hanya jatuh pada satu pihak.
Lebih dari itu, publik perlu diajak memahami bahwa investasi besar ini bukan semata demi keindahan kota, melainkan demi keselamatan, keandalan layanan, dan nilai ekonomi jangka panjang.
Hutan kabel adalah warisan masa lalu yang kini membayangi masa depan. Membenahinya bukan sekadar soal merapikan kabel, melainkan pernyataan keseriusan dalam membangun kota yang beradab dan berkelanjutan.
Prosesnya memang mahal dan tidak nyaman, layaknya operasi besar pada tubuh kota. Namun, menunda hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Langit kota kita telah terlalu lama terbelit. Kini saatnya kita berani menyibaknya kembali, agar kota-kota Indonesia dapat bernapas lega dan menatap masa depan dengan wajah yang lebih tertata.
***
*) Oleh : Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Program Studi Teknik Industri, Universitas Bung Hatta.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |